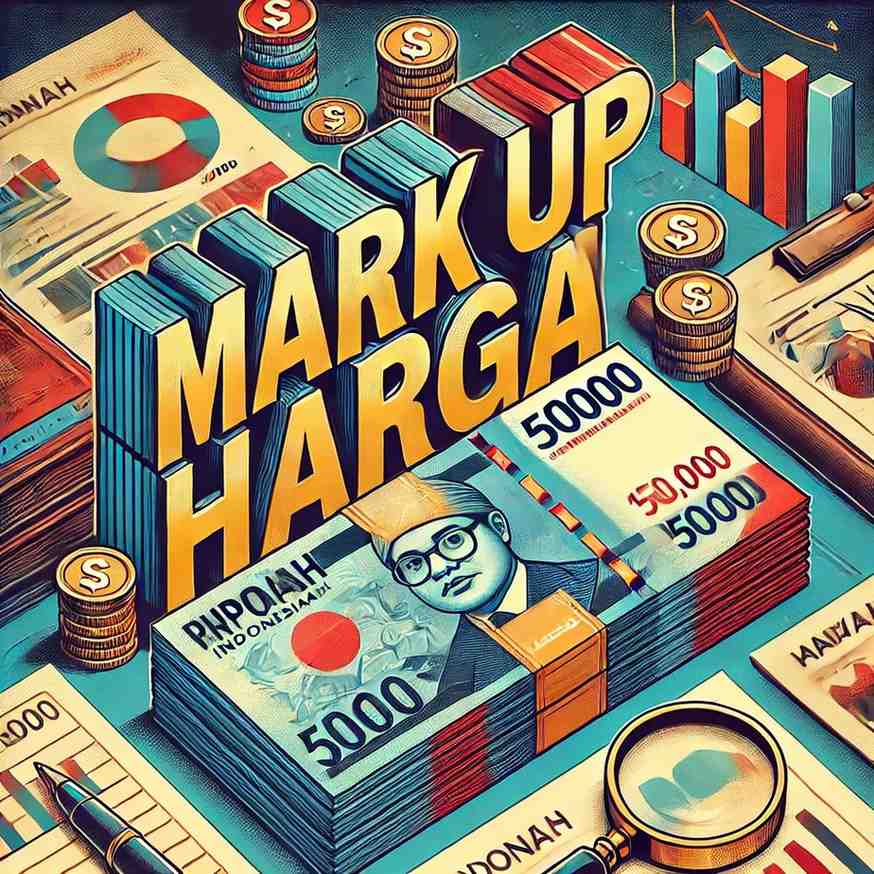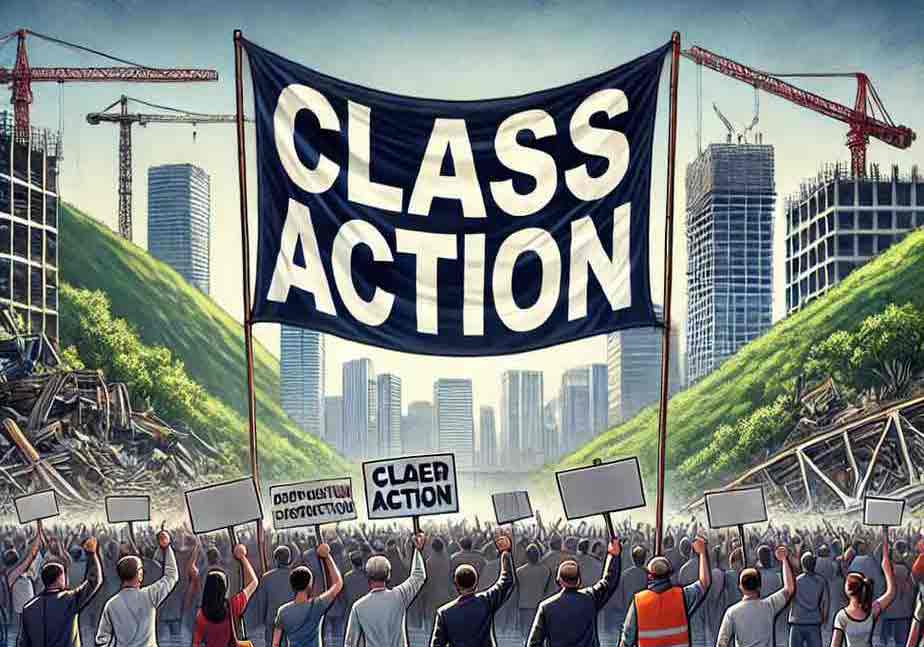Pedamaran, sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menjadi saksi diam dari konflik agraria yang tak kunjung usai. Namun, sengketa di sini bukan semata soal “siapa pemilik sah tanah”—melainkan kisah yang lebih dalam: benturan antara adat leluhur, ekspansi industri sawit, dan kehancuran bentang alam rawa gambut yang menghidupi ratusan tahun budaya lokal. Melansir berita dari situs pantauindonesia berikut ini ulasan terkait.
Dari Tanah Ulayat ke Sertifikat Konsesi: Jejak Dualisme Kepemilikan
Masyarakat adat Pedamaran—yang terdiri dari keturunan Komering, Ogan, dan sebagian Bugis perantauan—sejak dahulu mengelola tanah berdasarkan hukum adat. Mereka membuka kebun, menangkap ikan di rawa, dan menjaga kawasan hutan untuk kebutuhan ritual dan keseharian.
Namun, sejak awal 2000-an, pemerintah daerah mulai memberikan izin konsesi kepada perusahaan sawit dan HTI (Hutan Tanaman Industri), yang sebagian tumpang tindih dengan wilayah yang secara adat dianggap sebagai tanah ulayat. Hal ini menimbulkan konflik hak kelola, di mana tanah yang secara turun-temurun dikuasai masyarakat adat tiba-tiba berstatus milik perusahaan.
“Kami punya batas tanah yang diketahui dari nenek moyang, tapi kenapa tiba-tiba ada bulldozer masuk?” — ungkap salah satu tokoh adat dari Desa Pedamaran VI.
Konflik Tiga Arah: Masyarakat, Perusahaan, dan Pemerintah
Sengketa lahan di Pedamaran bukan hanya soal dua pihak, melainkan konflik tiga arah:
-
Masyarakat lokal dan adat merasa dirampas hak leluhurnya.
-
Perusahaan swasta mengklaim telah mendapatkan izin resmi dari negara.
-
Pemerintah daerah dan pusat sering berada di posisi ambigu—di satu sisi harus menarik investasi, di sisi lain menghindari konflik sosial.
Akhirnya, muncul berbagai bentuk perlawanan: dari protes damai hingga penolakan fisik terhadap alat berat. Dalam beberapa kasus, terjadi penahanan warga yang dianggap mengganggu aktivitas perusahaan, meski mereka sedang berkebun di lahan yang sudah digarap puluhan tahun.
Rawa Gambut yang Menyimpan Luka
Pedamaran dikenal memiliki hamparan rawa gambut luas yang dulunya menjadi sistem penyangga ekologi dan sumber pangan lokal. Namun pengeringan gambut demi perkebunan skala besar menyebabkan:
-
Turunnya permukaan air tanah.
-
Rusaknya sistem tangkap ikan tradisional.
-
Meningkatnya titik api saat musim kemarau.
Dampaknya bukan hanya ekologis, tetapi juga sosial dan budaya. Banyak anak muda Pedamaran kini meninggalkan kebiasaan lama mencari ikan atau menyadap getah karena rawa tempat mereka belajar hidup telah hilang.
Ketika Peta Digital Tidak Mewakili Realitas Emosional
Dalam banyak sengketa, peta digital dan sertifikat sering jadi alat pembuktian formal. Namun di Pedamaran, ada “peta” lain yang lebih kuat: peta emosi kolektif dari ratusan keluarga yang merasa tanah mereka dihapus dari sejarah. Dikutip dari situs Pantau Indonesia bahwa ‘Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 80% konflik agraria di Indonesia tidak terselesaikan dengan baik, yang berpotensi memicu ketegangan sosial.’
Pendekatan hukum modern sering kali mengabaikan realitas ini. Padahal, setiap pohon sagu, setiap danau kecil, punya nama dan cerita. Ketika semuanya digusur atas nama pembangunan, hilang pula identitas dan keterikatan emosional masyarakat terhadap ruang hidupnya.
Solusi Parsial yang Tak Menyentuh Akar
Pemerintah daerah beberapa kali memfasilitasi mediasi, namun sebagian besar berujung pada solusi parsial, seperti:
-
Redistribusi lahan kecil di pinggir konsesi.
-
Program CSR dari perusahaan.
-
Penetapan kampung adat (yang seringkali tidak diakui oleh UU secara kuat).
Namun akar masalah—yaitu ketimpangan kuasa atas penentuan ruang—tidak pernah benar-benar diselesaikan. Selama peta konsesi ditentukan tanpa melibatkan masyarakat adat sejak awal, maka konflik seperti di Pedamaran akan terus terulang.
Pelajaran dari Pedamaran: Melihat Sengketa sebagai Cermin Bangsa
Sengketa lahan di Pedamaran adalah gambaran kecil dari ribuan konflik agraria di Indonesia. Namun ada hal unik dari kasus ini:
-
Ia mempertemukan tiga dunia: adat, kapital, dan ekologi.
-
Ia menunjukkan bahwa konflik bukan hanya soal hukum, tapi juga nilai dan identitas.
-
Ia membuktikan bahwa pembangunan tanpa memori bisa menjadi penghancur yang lebih kejam dari senjata.
Penutup: Membaca Ulang Tanah Sebagai Ingatan
Tanah di Pedamaran bukan sekadar komoditas. Ia adalah ingatan kolektif, ruang hidup, dan identitas sosial. Ketika negara dan industri gagal mengakui dimensi ini, maka setiap pembangunan hanyalah penggusuran yang diselimuti narasi kemajuan.
Pedamaran mengingatkan kita bahwa tanah bukan hanya milik hukum, tapi juga milik hati. Dan ketika hati-hati itu tersingkir dari peta, maka yang muncul adalah konflik yang tak kunjung reda.